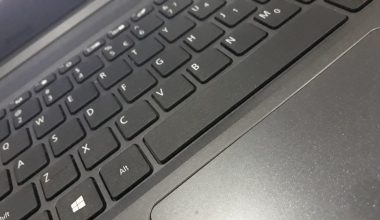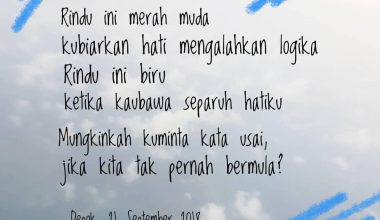The Unspoken Love
Oleh: Hera Budiman
10.15 pagi
“Honey, jangan lupa breakfast.” Terkirim satu pesan di whatsapp yang tadi sempat dibaca pengemudi mobil silver itu, sebelum lampu lalu lintas kembali hijau. Dia mengemudikan mobil ditemani James Arthur dengan “Say You Won’t Let Go”, membayangkan seandainya si pemberi pesan di whatsapp tadi bisa seromantis pelantun lagu ini.
Tidak lama, dia sampai di tempat yang dituju. Tempat parkir masih lengang Hanya ada beberapa mobil berjajar rapi di bagian depan mal besar itu. Tidak aneh sebenarnya, mengingat mal besar itu baru dibuka jam 10 pagi, kecuali pasar swalayan besar yang ada di lantai basement, yang memang dibuka satu jam lebih awal.
Mobil berwarna silver itu melaju memasuki area parkir, tidak terlalu cepat tidak pula lambat. Sepertinya si pengemudi tidak tergesa-gesa. Setelah mengambil karcis parkir, dia memutari bangunan mal 3 lantai itu. Tempat parkir belakang yang kemudian dia pilih untuk menghentikan si silver, teman setia yang selalu menemani aktivitas perempuan itu.
Ya, pengemudi mobil itu ternyata seorang perempuan, dengan wajah alami tanpa make-up penuh, hanya olesan tipis bedak dan sapuan lipstik berwarna nude. Namun kisah hidup perempuan bernama Re itu ternyata tidak sesederhana riasan wajahnya. Alami mungkin, tapi begitu berwarna. Terutama di satu setengah tahun ini. Seandainya mobil silver itu bisa berbicara, mungkin ia akan membutuhkan waktu panjang untuk bercerita tentangnya. Tentang kegigihan Re menjalani mimpi-mimpi hidupnya dan mewujudkannya dalam genggaman. Tentang sifat keras kepalanya memegang prinsip yang diyakininya dalam hidup. Tentang keyakinannya bahwa semua bisa dijelaskan dengan logika. Bahkan tentang perasaan gamang yang dia rasa ketika logika itu diporak-porandakan oleh satu hal. Satu hal yang mengantarkannya pada hari ini, di sini.
***
Beberapa jam sebelumnya
“Yakin mau pergi?” Andi bertanya.
“Ya,” jawaban tegas yang Re beri walau sebenarnya dia sendiri gamang.
“Bisakah kamu pertimbangkan lagi?” Andi masih berharap Re bisa mengubah keputusannya. Bukan bermaksud menghalangi keinginan perempuan yang dia sayangi itu, Andi hanya berharap Re tidak pergi hari ini.
“Please, kita sudah bahas itu berulangkali,”
“Somehow kamu tidak berubah. Keras kepala.” Kalimat itu diucapkan pelan dengan mata masih tertuju pada Re, perempuan yang di mata Andi tidak hanya cantik tetapi juga cerdas. Andi hanya tersenyum tipis, entah apa yang ada di balik senyuman itu.
“Anak-anak?” tanya Andi kemudian.
“Anak-anak memilihmu,” Re menjawab pelan, jawaban yang sebenarnya sangat tidak disukainya.
“Mereka berharap tidak perlu memilih,” kata Andi. Dengan tatapan yang masih berharap Re tiba-tiba berubah pikiran.
“Aku tidak mau terlambat, aku harus pergi sekarang,” Re melihat dengan cepat waktu di telpon genggamnya.
Sebenarnya Re tidak akan terlambat, dan dia tahu itu. Masih ada waktu yang dia punya sekalipun jalanan pagi itu macet. Dia hanya tidak nyaman berlama-lama membahas hal yang sama. Bukan karena dia tidak peduli dengan anak-anaknya dan lelaki yang merupakan ayah mereka. Bukan itu.
“Jam berapa?” tanya lelaki itu akhirnya.
“Nanti anak-anak aku jemput jam 4 sore, mudah-mudahan ga macet,” jawab Re cepat sambil masuk ke mobilnya.
“Ok, please telpon kalau anak-anak mau dijemput,” Andi pun masuk ke mobil hitamnya. Mereka akhirnya pergi ke arah yang berbeda.
***
10.20 pagi
Re masih belum mematikan mesin setelah mobilnya terparkir di tempat yang sedikit teduh. Dia membuka ray.ban dan menyimpannya di tempat biasa dan kemudian dimasukkan ke dalam tasnya. Tidak tergesa-gesa. Sedikit gugup, tepatnya. Masih duduk di belakang kemudi, dia berpikir tentang segala sesuatu yang mungkin terjadi. Bukan tentang pertemuan yang membuatnya gugup sekaligus excited. Tapi tentang kemungkinan adanya satu bab baru yang akan dia jalani dalam hidup. Seseorang dari masa lalu yang akan dia temui hari ini, di tempat ini. Seseorang yang membuatnya berani mencoba hal baru, sesuatu yang mungkin akan menjadi satu warna dalam pelangi hidupnya.
Akhirnya, dimatikan juga mesin mobil itu. Re melangkah keluar dengan membawa tas tangan biru. Dia tahu dia datang lebih awal dari jam yang dijanjikan. Tapi, tak mengapa. Dia putuskan untuk mencari tempat yang nyaman sekaligus memesan makanan kecil. Perutnya yang baru diisi secangkir kopi sejak pagi mulai meronta ronta rupanya. Waktu menunjukkan jam 10.20, masih ada sekitar satu jam bagi dia untuk menikmati brunch, sebelum seseorang dari masa lalu itu datang.
Dengan langkah anggun tapi menyiratkan ketegasan seorang perempuan cerdas, Re memasuki salah satu tempat makan di dalam mal. Di sisi kanan dari pintu masuk mal, terdapat beberapa restoran dengan berbagai pilihan jenis cuisine, mulai dari makanan khas Indonesia, makanan Eropa, makanan Jepang, bahkan restoran yang menyajikan pilihan jenis pancake. Di hari kerja seperti hari ini, mal itu biasanya ramai pengunjung pada saat jam makan siang.
Re akhirnya memasuki salah satu tempat makan itu, restoran yang disepakati untuk rendevouz dengan teman masa lalunya. Restoran yang sering dia masuki. Dia memilih tempat duduk yang dirasa nyaman. Dari tempat duduk di pojok kanan itu, dia bisa melihat ke arah luar. Masih sepi. Hanya beberapa orang terlihat duduk menikmati sarapan yang terlambat atau mungkin juga makan siang yang terlalu cepat. Tidak lama kemudian, seorang pelayan restoran menghampiri. Sambil memberikan daftar menu, pelayan itu menyapa dengan ramah.
“Sudah siap memesan sekarang, Kak?’
“Mushroom puff pastry dan hot chocolate.” Re memesan makanan tanpa membuka daftar menu yang diberikan pelayan restoran.
Setelah mengulangi menu yang dipesan perempuan itu, sang pelayan pergi. Hanya anggukan kecil dan senyum yang diberikan Re.
“Terima kasih,” ucapnya.
Sambil menunggu pesanan datang, Re melihat telpon genggamnya. Lalu membuka whatsapp, membaca beberapa pesan yang masuk dan membaca ulang obrolan Re dengan lelaki yang akan dia temui hari ini.
***
Satu tahun yang lalu
“Udah baca puisi yang baru aku posting, belum?” Sebuah pesan di whatssapp masuk.
“Belum. Tentang apa?” Re kemudian mengetik jawaban pesan itu
“Baca aja dulu. That’s for you.” Ada rasa yang belum sepenuhnya Re pahami.
Meskipun baru enam bulan berteman dengan Andre lewat Facebook, Re merasa sudah cukup lama mengenal lelaki itu. Awalnya hanya saling sapa di fanpage komunitas sastra. Kemudian, komunikasi mulai intens dengan saling memberi komentar di postingan masing-masing. Ketertarikan yang sama pada sastra membuat mereka lebih dekat. Komunikasi pun berlanjut setelah mereka saling bertukar nomor telpon.
Setelah sekian lama, obrolan pun tidak hanya tentang dunia sastra tapi mulai ke arah yang lebih pribadi. Bagi seorang Re, Andre adalah orang yang bisa memahami tulisan-tulisannya. Andre mampu membaca dirinya. Tidak hanya itu, setiap puisi yang Andre posting mampu membuat Re tersentuh dan meleleh hatinya. Betapa tidak, Re tidak pernah mendapatkan kata-kata romantis itu dari Andi. Ya, Andi yang lulusan teknik itu tidak pernah tertarik membicarakan sastra.
Ironisnya, Andi yang Re pilih menjadi ayah anak-anaknya justru karena karakternya yang tegas, visioner, bertanggungjawab, dan mandiri. Dulu, pemberian bunga dan kata-kata romantis bagi Re adalah hal lebay yang tidak perlu. Re merasa Andi mampu mengimbangi karakternya yang juga terbiasa mandiri dan selalu melihat jauh ke depan. Siapa sangka, di usia Re yang mendekati kepala empat, dia justru mendambakan hal lain dari Andi.
Kata-kata romantis dan puisi-puisi dari Andre membuat Re merasa hidupnya lebih berwarna. Sulit bagi Re memahami rasa yang bergejolak setiap kali dia berkesempatan mengobrol dengan Andre, meskipun itu sebatas online. Ingin sekali Re mengingkari rasa yang ada, tetapi seperti sia-sia. Semakin kuat Re berusaha melupakan, semakin sulit nama itu hilang dari ingatannya.
***
10.30 pagi
“Silakan, selamat menikmati.” Pelayan restoran datang membuyarkan lamunan Re.
“Terima kasih,” jawab Re.
Sambil menikmati brunch dengan setengah hati, Re tidak berhenti memikirkan tindakannya, keputusan yang dia ambil di saat dia sendiri tidak yakin dengan perasaannya. Kepalanya seakan tidak berhenti berputar. Benarkah langkah yang diambilnya? Benarkah rasa itu dikendalikan oleh hati? Lalu, di mana logika berperan? Semua pertanyaan itu terus datang menggoda logika.
Untuk perempuan cerdas seperti Re, yang semua hal harus bisa dijelaskan dengan logika, tindakannya kali ini benar-benar ceroboh. Dia biarkan rasa itu berkembang dan tumbuh menutup segala alasan yang disodorkan akal sehat. Re berjudi dengan kemungkinan. Dia seakan menerima tantangan yang bahkan bisa jadi itu dapat memberikan hasil terburuk dalam hidupnya. Kemungkinan yang akan mengubah kehidupannya sekarang. “Apa yang kamu cari, Re?” Pertanyaan itu datang lagi dan lagi, mengusik logika dan nurani Re.
Beep, suara dari telpon genggamnya. Sebuah pesan whatsapp masuk.
“Honey, gimana meetingnya? Nothing to lose aja ya.” Pesan dari Andi rupanya. Pertanyaan itu menusuk nurani Re. Bagaimana tidak? Alasan itu yang diberikan pada Andi tentang pertemuan ini. Tentang kebohongannya mengatakan jika ini pertemuan Re dengan teman dari penerbit, untuk membicarakan naskah buku Re.
“Whatever makes you happy, honey.” Andi membolehkan Re pergi karena dia tahu menulis adalah dunia Re. Kebohongan pertama sejak pernikahan mereka. Kebohongan Re untuk lelaki yang telah mendampinginya selama 17 tahun. Rasa sesak di dada menghentikan Re meneruskan brunch. Rasa sesak karena kebodohannya. Rasa sesak karena kebohongan yang telah diperbuatnya. Rasa sesak karena penyesalan mendalam.
“Ya Tuhan. Apa yang sedang aku lakukan? This is not me.” Pertanyaan itu berkecamuk di dada. Di titik ini, Re mulai membiarkan logika mengambil alih rasa. Dia terus meyakinkan diri jika rasa yang ada untuk Andi itu nyata. Andre hanya memberikan rasa sesaat, rasa semu. Re meyakinkan diri jika dia jatuh hati pada kata-kata, bukan pada si perangkai kata.
Dengan tergesa, Re menyudahi brunch dan meninggalkan tempat makan itu setelah membayar tagihan.
11.00 pagi
Di tempat parkir, di dalam sebuah mobil silver dengan mesin yang menyala, seorang perempuan duduk di belakang kemudi. Dia tuliskan di note telpon genggamnya, “Takkan kubiarkan hati mengkhianati logika karena rasa itu bukan sekadar pekerjaan hati.”